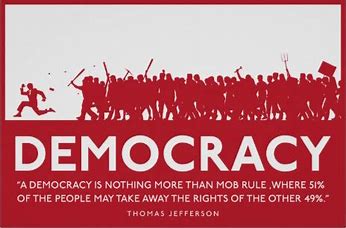Oleh : Prof. Hafid Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM RI)
Disadari atau tidak, sejak 1998, Indonesia telah memilih jalan demokrasi liberal yang didikte oleh Hukum Darwin, survival of the fittest. Yang kuatlah yang menang dan yang lemah akan punah selamanya. Demokrasi ternyata tidak mengenal belas kasihan kepada mereka yang miskin.
Tidak terasa, kini Indonesia telah melewati seperempat abad perjalanan sejarahnya berubah dari sistem pemerintahan yang berciri otoritarian selama 32 tahun ke tatanan pemerintahan yang demokratis.
Tuntutan memilih jalan demokrasi di penghujung abad ke-20 itu, dipicu oleh memburuknya keadaan ekonomi nasional sebagai akibat krisis moneter yang telah melanda Thailand pada pertengahan 1997. Krisis ini kemudian meluas ke kawasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita pada 1998 mencapai -16,54% (hyperinflation and depression).
Angka penduduk miskin tiba-tiba berlipatganda menjadi sekitar 79,4 juta orang atau 39,1% dari 202 juta penduduk, dan PHK terjadi di mana-mana (BPS, 1998).
Kegoncangan ini kemudian membawa pula kegoncangan sosial dan politik dan krisis multidimensi yang memaksa era kekuasaan Orde Baru yang didukung oleh kekuatan bersenjata harus digantikan dengan supremasi sipil dalam payung negara demokrasi.
Pada waktu itu kita belum siap berdemokrasi yang mengharuskan, misalnya adanya pembagian kekuasaan yang berimbang antara kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif, antara pusat dan daerah, adanya kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan media, dst. Yang terjadi pada masa itu hanyalah sebuah keberanian untuk segera berubah.
Akumulasi tuntutan reformasi itu dipicu oleh tertembaknya empat mahasiwa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Ibarat sumbu petasan, peristiwa itulah yang meledakkan perubahan sosial-politik.
Peristiwa ini merupakan pintu gerbang lahirnya era demokratisasi yang telah mengantar pergantian kepemimpinan nasional secara amat dramatis. Euforia demokratisasi, HAM dan kebebasan berekspresi seakan tidak terelakkan.
Bahkan kebebasan seperti itu dinilai telah melewati batas-batas kepatutan menurut ukuran-ukuran negara paling bebas dan paling demokratis sekalipun. Kalau dulu dikenang semangat heroisme sekali merdeka tetap merdeka, sekarang semangat itu bermakna ”sekali merdeka, merdeka sekali.”
Sebagai keputusan bersejarah yang emosional, kemarahan yang tidak terbendung, tentu tidak dimungkinkan terdapat pemikiran-pemikiran rasional yang sejuk untuk memperhitungkan segala konsekuensi yang akan ditimbulkan atas keputusan itu.
Boediono dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengemukakan bahwa sejumlah studi juga menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu penting bagi keberlanjutan demokrasi.
Demokrasi Gagal
Suatu studi yang banyak diacu menyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-90, rezim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan per kapita 1500 dolar (dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity, 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun. Singkatnya, jika negara itu miskin, demokrasinya akan gagal (Tempo, 24/02/2007).
Sejumlah studi lain memperlihatkan, dalam dua-tiga dekade terakhir, dari 191 negara berdaulat, 117 di antaranya yang memilih haluan politik sebagai negara demokrasi.
Kasus India, Brazil dan Mauritius terlihat pembangunan ekonominya cenderung semakin membaik setelah berdemokrasi.
Sebaliknya, Tunisia dan Libya, keadaanya semakin terpuruk setelah berdemokrasi. Yang amat tragis, Uni Soviet sebagai negara adidaya, ternyata ketika pada akhir 1980-an, pemimpinnya, Mikhail Gorbachev, merestrukturisasi negaranya melalui kebijakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (reformasi), hasilnya negara ini bubar dan pecah menjadi 15 keping-keping negara baru pada akhir 1991.
Sebaliknya, Bank Dunia (2022) melaporkan pula banyak negara yang maju, damai dan sejahtera tanpa berdemokrasi, seperti: Chile dengan GDP per kapita $12.700, Hong Kong ($25.200), Singapore ($28.000) dan Korea Selatan ($13.600), China ($12.732), dst.
Posisi Indonesia di mana? Apakah kita akan tetap merawat pilihan kita di jalan demokrasi seperti ini dengan resiko Indonesia terancam bubar (Bank Dunia Indonesia Rising Dvide 2015), semakin terpecah dan dapat bubar pada 2030 seperti prediksi Prabowo Subianto (BBC, 24/03/2018), ataukah kita merenung sejenak, are we on the right track, dengan memetik pelajaran berharga dari kehidupan semut.
Belajar dari Kehidupan Semut
Secara statistik, penduduk dunia kini sudah mencapai delapan miliar jiwa (Worldmeter, 2023). Mereka tersebar di 195 negera, dua di antaranya yang belum menjadi anggota PBB yakni Palestina dan Holy See. Dari jumlah itu, ada negara yang memilih jalan demokrasi, ada yang diktator-otoriter, dan ada pula berada di antaranya. Corak kehidupannya, mirip dengan pola kehidupan semut.
Analogi kehidupan itu, pertama kali diungkapkan oleh seorang pemenang Hadiah Nobel di bidang Biokimia asal Belgia, Ilya Prigogine, yang telah meneliti pola kehidupan semut. Dalam artikelnya “The Die is not Cast” (UNESCO, 1999) melukiskan pola dan perilaku kehidupan semut, mirip pola kehidupan manusia.
Menurut Ilya, di alam raya ini terdapat sekitar 12000 jenis spesies semut yang sudah dikenal manusia. Kemungkinan masih terdapat jumlah yang lebih besar yang belum dikenal hingga dewasa ini. Yang menarik ditelaah lebih dalam adalah pola perilaku kehidupan semut tersebut.
Jika mereka hidup dalam koloni atau kelompok kecil perilakunya sangat individualistik. Mereka mencari makanan secara bebas kemudian membawa makanan itu ke sarangnya tanpa ada aturan.
Namun jika mereka hidup di koloni besar yang dapat bervariasi dari ratusan, ribuan hingga jutaan, maka mereka diatur oleh suatu sistem kontrol melalui auto catalytic reaction antarsemut yang kemudian melahirkan reaksi kimia yang berfungsi sebagai mediated exchange information yang mengatur tata kehidupannya.
Semakin besar jumlah semut dalam satu koloni maka semakin ketat mekanisme kontrolnya untuk mengatur dirinya dan distribusi makanannya. Sekiranya ada semut yang melanggar aturan dengan berperilaku semaunya maka reaksi kimia tadi akan meracuninya dan menyebabkannya menjadi buta dan kemudian dimangsa oleh semut lainnya. Begitulah rentang pola hidupnya dari corak individualistik ke pola hidup berkelompok.
Tiga Polarisasi
Seperti halnya semut, manusia mempunyai pula tiga pola polarisasi kehidupan.
Polarisasi pertama adalah manusia yang hidup di dunia pertama yang umumnya berada di AS, Eropa Barat dan Scandinavia. Sumber-sumber ekonominya relatif lebih maju dibanding di belahan bumi lainnya.
Jumlah penduduknya relatif lebih kecil dan bahkan banyak yang tingkat pertumbuhannya di bawah nol. Pola hidup warganyamenjunjung tinggi kebebasan individu dengan nilai-nilai demokrasinya.
Sebagai gambaran, pada pemilu Presiden AS 2000 adalah pertarungan antara calon presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, melawan calon dari Partai Republik, George W. Bush. Bush menang tipis dalam pemilu ini dengan memperoleh 271 suara elektoral, sementara Gore hanya mendapatkan 266 suara elektoral (selisih lima suara).
Ini kemudian memunculkan sengketa perhitungan suara, namun, keputusan Mahkamah Agung dalam penanganan kasus ini, pada 12 Desember 2000 dimenangkan Bush yang kemudian mengantarnya menjadi Presiden AS ke-43.
Polarisasi kedua adalah pola perilaku kehidupan masyarakat di belahan dunia kedua yakni di negara-negara sosialis, seperti China, Korea Utara, Cuba, dsb. Penduduknya berjumlah relatif besar dengan sumber daya ekonomi yang terbatas memaksa pola kehidupan masyarakatnya membatasi kebebasan individu. Masyarakat di blok ini yang dipentingkan adalah hak-hak kolektifnya.
Di China misalnya, sekiranya ada demonstrasi yang menentang kebijakan publik yang diberlakukan pemerintah, tidak menutup kemungkinan tragedi pembantaian massal dapat terulang lagi, seperti terjadi di lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989.
Dari sudut pandang kehidupan politiknya, misalnya, di Korea Utara yang berpenduduk 25,97 juta jiwa (2021), ketika melaksanakan pemilu itu pada 9 Maret 2014, hasilnya telah mengantar kembali kemenangan mutlak, 100 persen, ke Presiden Kim Jong Un, tanpa ada seorang pun yang memilih calon presiden lain, karena memang hanya dia calon satu-satunya. Inilah ciri pemerintahan pada negara yang berhaluan politik totalitarian dictatorship.
Polarisasi ketiga, Indonesia sebagai negara yang berhaluan politik yang berdasar pada falsafah Pancasila tentu tidak akan memilih model sistem pemilu seperti di Korea Utara, atau pun seperti di AS atau di negara-negara yang berhaluan politik kapitalis.
Namun, corak haluan politiknya adalah mempertemukan semua nilai-nilai yang dipandang positif dari dunia kapitalis dan dari dunia sosialis.
Pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, Indonesia memperkenalkan istilah “the third world” yang kemudian mengantar lahirnya kubu negara-negara non-blok yang tidak memihak ke dunia pertama dan dunia kedua.
Disadari atau tidak, sejak 1998, Indonesia telah memilih jalan demokrasi liberal yang didikte oleh Hukum Darwin, survival of the fittest. Yang kuatlah yang menang dan yang lemah akan punah selamanya. Demokrasi ternyata tidak mengenal belas kasihan kepada mereka yang miskin.